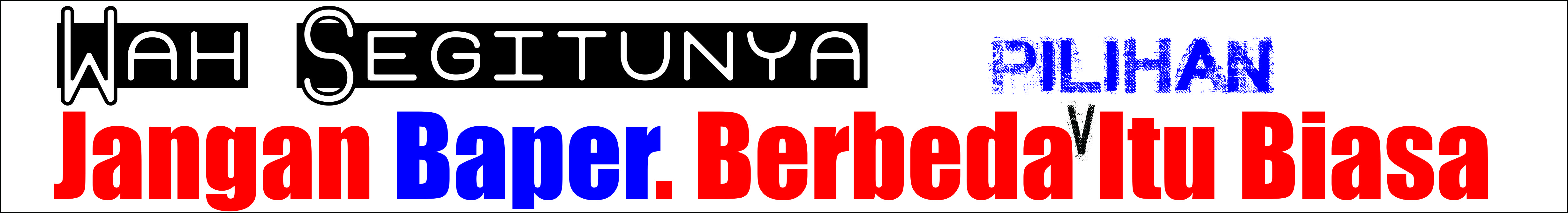Muasal Sebutan Haji Jadi Gelar
oleh : *MAHRUS ALI,
*Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia
SUARAKALTIM.COM-Banyak yang mengira sebutan ‘haji’ dan ‘hajjah’ hanya marak di kalangan orang Melayu (Indonesia, Malaysia, Brunai dan Thailand Selatan) yang telah menjalankan ibadah rukun Islam kelima, yaitu haji. Tidak, ternyata di bagian lain dunia ini ada juga bangsa yang menggunakan sematan yang sama.
Gelar atau sebutan haji yang aslinya dari bahasa Arab ini memiliki versi sesuai bahasa lokal negara umat Islam yang menggunakan. Dalam bahasa Pashto ditulis: حاجی, bahasa Albania: Haxhi, Bulgaria: Хаджия, Kurdi: Hecî, Serbia/Bosnia/Kroasia: Хаџи atau Hadži, Turki: Hacı, Hausa: Alhaji dan bahasa Romania: hagiu, Yunani: Χατζής.
Di beberapa negara, gelar haji bahkan diwariskan turun-temurun menjadi nama trah atau nama keluarga seperti Hadžiosmanović dalam bahasa Bosnia yang berarti ‘Bani Haji Usman’ alias ‘Trah Haji Usman’. Gelar haji juga digunakan di negara-negara Balkan yang pernah dikuasai Imperium Usmani (Bulgaria, Serbia, Yunani, Montenegro, Makedonia dan Romania) bagi yang sudah pernah berziarah ke Tanah Suci. Namun di negara-negara Islam seperti Saudi, Mesir, Pakistan, Republik Islam Iran dan lainnya, hal demikian tidak lazim saat ini.

Di tanah air, sebutan haji sudah menjadi gelar yang berasosiasi pada status sosial dan tingkat keberagamaan seseorang. Mengapa demikian? Bagaimana muasalnya melaksanakan rukun Islam mendapatkan gelar, sementara pelaksana rukun Islam lain seperti para wajib zakat, puasa, dan shalat tidak meninggalkan gelar apapun?
Berikut adalah penulusuran berdasarkan catatan sejarah dan bukti-bukti kebijakan yang pernah dikeluarkan pemerintah kolonial terhadap umat Islam Nusantara yang melaksanakan ibadah haji.
Bahwa benar pada zaman dahulu, ketika situasi kota Mekkah mencekam akibat pertikaian antar perebut kekuasaan, sebutan ‘haji’ pernah disematkan kepada mereka yang selamat kembali pulang. Hal itu terjadi sekitar tahun 654 H/ 1276. Saat itu kota Mekkah terputus dengan dunia luar, ditambah kekacauan yang meluas hingga tidak ada tertib sosial, sehingga para jemaah haji berangkat ke Masjidil haram dan Arafah, Mina Muzdalifah seperti berangkat ke medan perang. Dalam keadaan demikian, sekembalinya ke perkampungan suku masing-masing mereka dielu-elukan dengan sebutan “Ya Hajj, Ya Hajj”. Maka berawal dari itu, setiap orang yang pulang haji diberi gelar “Haji”.
Kejadian tersebut berlangsung tidak sampai bertahun-tahun karena ketika situasi normal kembali, di kalangan masyarakat Arab hingga hari ini tidak pernah lagi ada sebutan haji bagi yang telah melaksanakan ibadah haji. Haji, tak ubahnya amalan rukun Islam lain seperti shalat, zakat dan puasa, tidak meninggalkan sebutan atau gelar.
Hal ini berbeda 180 derajat dengan masyarakat di Indonesia yang justru menggunakan sebutan haji atau biasa disingkat ‘H’ atau “Hj’ pada KTP, SIM, Kartu Nama bahkan dimanfaatkan untuk kampanye pemilihan umum atau kepala daerah. Jika di tempat asalnya orang yang berhaji tidak lagi menggunakan sebutan haji, lalu sejak kapan orang Indonesia menggunakan sematan ‘haji’ di sebelah namanya? Mengapa ketika di sumbernya tidak digunakan justru di sini semakin dibangga-banggakan?
Berdasarkan penelusuran, pernah ditemukan perintah penggunaan ‘gelar’ haji bagi para pelaksana haji nusantara. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintahan Kolonial Belanda dalam Staatsblad tahun 1903 dan saat jemaah haji makin meningkat sejak tahun 1911, pemerintah Hindia Belanda mengkarantina mereka hendak pergi haji maupun setelah pulang haji di Pulau Cipir dan Pulau Onrust, Kepulauan Seribu, Jakarta. Pada saat di karantina kedatangan, dengan alasan kamuflase “untuk menjaga kesehatan”, kadang saat ditemukan adanya jemaah haji yang dinilai berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda, diberi suntik mati diam-diam. Maka tak jarang banyak yang dimatikan di karantina pulau Onrust dan Cipir.
Belanda mencatat dengan detail nama dan asal wilayah jemaah Haji dan untuk memudahkan pengawasan para jemaah haji, pemerintah Hindia Belanda memberi cap (gelar) yang wajib digunakan kepada mereka yang baru kembali dari Mekkah, yaitu “Haji”. Begitu terjadi pemberontakan di wilayah tersebut, Pemerintah Hindia Belanda dengan mudah menunjuk tersangka, karena di depan nama mereka sudah tercantum gelar haji.
Ketentuan ini muncul setelah muncul usaha perjuangan kemerdekakan Indonesia sebagian besar dipimpin para haji. Mereka yang ditangkap, diasingkan, dan dipenjarakan adalah yang memiliki cap haji, seperti Pangeran Diponegoro sepulang haji melakukan perlawanan terhadap Belanda. Imam Bonjol ketika pulang haji melakukan perlawanan, KH Muhammad Darwis Ahmad Dahlan pulang haji mendirikan Muhammadiyah, KH Hasyim Asy’ari mendirikan Nadhlatul Ulama, Haji Oemar Said Cokroaminoto dan Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam. Hal-hal seperti inilah yang merisaukan Belanda. Maka salah satu upaya Belanda untuk mengawasi dan memantau aktivitas serta gerak-gerik para haji ini adalah dengan mengharuskan penambahan gelar haji di depan nama orang yang telah menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air.
Yang dilakukan Belanda tersebut hanya menegaskan hal yang sudah berlaku di tengah masyarakat, sehingga tidak dapat dikatakan kebijakan tersebut sebagai permulaan digunakannya sematan haji, sebagaimana disebut sementara pihak.
Jika penelusuran dilakukan lebih mendalam akan kita dapati sesungguhnya umat Islam di Nusantara ini sudah menggunakan sebutan haji sejak awal sebelum berdirinya kerajaan Islam Nusantara. Diceritakan dalam babad atau kronika cerita rakyat, putra-putri Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, yaitu Walangsungsang bersama adiknya Rarasantang berangkat ke Mekkah (diperkirakan antara tahun 1446-1447) untuk menunaikan ibadah haji dan belajar ilmu agama Islam. Dalam perjalanan ibadah haji itu, Rarasantang dinikahi oleh Syarif Abdullah, Sultan Mesir dari Dinasti Fatimiyah, dan berputra dua orang yaitu Syarif Hidayatullah (1448) dan Syarif Arifin (1450). Sebagai seorang haji, Walangsungsang kemudian berganti nama menjadi Haji Abdullah Iman, sementara Rarasantang berganti nama menjadi Hajjah Syarifah Mudaim.
Menurut naskah sajarah Banten, pada tahun 1671 Sultan Ageng Tirtayasa mengirim putranya, Sultan Abdul Kahar, ke Mekkah untuk menghadap penguasa Mekkah sambil melaksanakan ibadah haji, lalu melanjutkan perjalanan ke pusat pemerintahan Turki Usmani. Karena menunaikan ibadah haji, Sultan Abdul Kahar kemudian dikenal dengan sebutan Sultan Haji.
Masih banyak kisah haji sebelum pemberlakukan Staatsblad tahun 1903 dan kesemuanya membawa sematan ‘Pak Haji’ – ‘Bu Haji’ bahkan sekembalinya dari Mekkah, mereka berganti baju kebesaran dari baju adat ke jubah dan surban dalam ritual agama. Pakaian ini oleh pemerintah kolonial disebut dengan ‘muhammadan costum’.
Nabi sendiri sepulang dari ibadah haji pada tahun 9 Hijriyah tidak bertambah sebutannya menjadi Haji Muhammad Rasulullah, tidak demikian. Demikian juga para sahabat yang tidak menuliskan

namanya menjadi Haji Abu Bakar, Haji Umar Ibnu Khattab, Haji Usman Ibnu Afan, Haji Ali Ibnu Abi Thalib, meski nama-nama tersebut sering menunaikan Ibadah Haji. Juga tidak kita kenal para ulama yang menulis enam kitab hadis legendaris seperti Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmudzi, Imam Nasa’i dan Imam Abu Dawud. Para Imam ahli fikih yang membentuk empat mazhab juga tidak sekali saja menuliskan nama dengan sebutan haji di kitab-kitab yang mereka tulis.
Akan tetapi sebutan haji di Bumi Nusantara, tanpa Staatsblad tahun 1903 pun sudah merata penggunaannya dan dimaklumi. Mungkin ini seperti ketika pertama kali muncul sebutan haji karena beratnya menembus Mekkah pada saat keadaan mencekam, perjalanan dari tanah air ke tanah suci juga mengancam jiwa. Dahulu, untuk sampai Mekkah dibutuhkan waktu enam bulan atau setahun baru kembali dengan moda transportasi perahu layar. Pun saat menggunakan moda kapal api, dua bulan di atas laut selama berangkat dan kembali dengan fasilitas kapal barang, tidak sedikit yang meninggal di atas dak akibat buruknya pelayanan. Masyarakat yang mengetahui demikan berat perjuangan untuk bisa sampai Mekkah dan kembali ke rumah, maka dapat dimengerti pemberian gelar itu diberikan. Jika karena itu alasannya, apakah masih patut sebutan itu diberikan ketika untuk ke Mekkah hanya memerlukan waktu sembilan jam saja? Masihkah beratnya medan perjalan menjadi variable dimakluminya sebutan itu?
Dengan memperhatikan alur munculnya sebutan haji dan hajjah bagi pelaksana rukun Islam kelima ini, dapat dikatakan bahwa sebutan haji dan hajjah adalah produk sejarah yang bersifat sosiologis, bukan ajaran agama yang bersifat dogmatis. Tidak dosa disematkan dan baik saja jika tidak digunakan. *