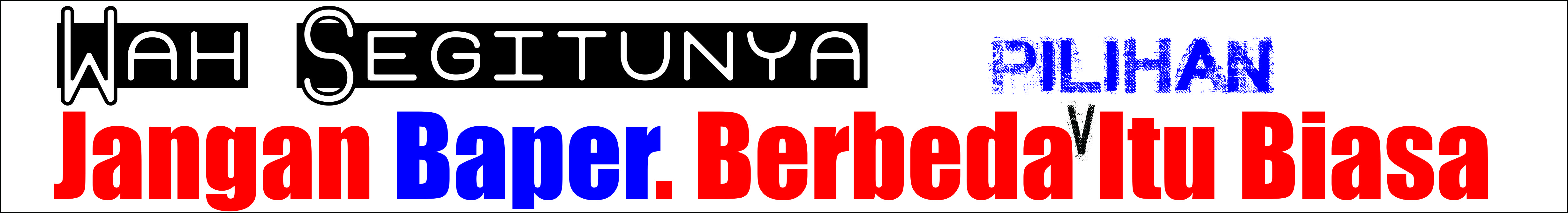PESAWAT mendarat di bandar udara Komoro, Dili.
Waktu itu, 23 November 1993.
Di landasan pacu saya menghirup nafas dalam-dalam. Dili tidak seromantis yang saya bayangkan. Panas sekali dan berdebu. Dari ketinggian dua ribu kaki, dari kaca jendela Fokker 100, Pulau Timor tampak berwarna kecoklatan, tandus, dan berbatu. Franscisco da Costa Gutteres sudah menunggu di sisi landasan. Bersamanya seorang lelaki kurus, yang kemudian saya kenal sebagai Domingus Saldanha, pemimpin perusahaan koran Suara Timor Timur (STT). Gutteres atau akrab dipanggil Sico, adalah kawan kuliah saya di Salatiga, Jawa Tengah. Dialah yang membujuk saya datang ke Dili dan bekerja di koran yang dikelola sepupunya, Salvador Ximenes Soares. Sico bekerja di kantor gubernur. Itulah sebabnya, dia bisa mencapai sisi landasan tempat pesawat parkir, menerobos penjagaan militer di ruang tunggu kedatangan. Tidak sembarang orang bisa melakukannya.
Dili, kendati panas, masih tersisip keindahan. Penyerbuan pasukan Indonesia ke Dili, 7 Desember 1975, masih menyisakan bangunan-bangunan bergaya art deco, peninggalan pemerintah kolonial Portugis. Kota ini terletak di tepi laut berhadapan dengan Pulau Alor di wilayah Nusa Tenggara Timur, Pulau Wetar di wilayah Maluku dan Pulau Atauro. Jika udara cerah, tiga pulau itu bisa dilihat dari dermaga Dili seperti kapal siluman raksasa.
Dili bukan kota besar, penduduknya hanya 100 ribu orang. Tapi, markas tentara terlihat di mana-mana. Pos satuan batalion teritorial berada di hampir setiap sudut kota. Dari Tasitolu di barat hingga Becora di timur, dari Farol di utara hingga Taibesi di selatan, Dili bak kota tentara. Tempat-tempat karaoke di malam hari dipenuhi tentara Indonesia. Seperti di Belfast, Irlandia Utara, bar-bar di sana dipenuhi tentara pendudukan Inggris.
Hari pertama bekerja di STT, saya diperkenalkan dalam rapat redaksi sore hari. Saya diminta jadi redaktur opini. Tugas saya memilih kiriman artikel opini, menulis tajuk, dan membuat pojok. Hari-hari berikutnya, melakukan reportase dan wawancara. STT bukan koran besar, oplahnya hanya 4.000. Gaji jelas tak besar, kendati saya harus bekerja sangat keras. Pukul 9.00 berangkat, pukul 3.00 esoknya baru pulang. Saya pulang naik motor sendiri, melintasi jalan-jalan Dili yang lengang. Merebahkan tubuh yang kelelahan di kamar kos yang panas.
Nyaris tak ada tempat hiburan. Satu-satunya bioskop yang ada bioskop Seroja, diambil dari nama operasi penyerbuan ke wilayah itu. Itu pun hanya memutar film-film lama produksi Indonesia. Jangan harap bisa nonton film mutakhir buatan Hollywood.
Televisi jadi hiburan satu-satunya. Menghabiskan malam-malam panjang di depan layar MTV Asia, jadi hal yang lazim. Rasa sepi menjadi musuh yang berat. Syukurlah, seorang kawan lama yang kelak menjadi istri saya, Hanita, rajin berkirim surat dan menelepon dari Bandung. Seringkali ada rasa sesal memilih terbang ke potongan pulau kecil di ujung Asia Tenggara ini.
AKSI mahasiswa Universitas Timor Timur terus berlangsung. Suatu hari, sekitar bulan Mei 1994, kampus kecil itu dikepung tentara dan polisi. Para mahasiswa berencana melancarkan protes ke kantor parlemen setempat. Aksi protes itu sebagai bentuk solidaritas terhadap seorang biarawati yang diperlakukan secara tidak sopan oleh seorang intel tentara di kampus yang sama sehari sebelumnya. Sang intel dipukuli dan berhasil lolos setelah mencabut pistol. Tapi, motornya tertinggal. Para mahasiswa menyimpannya sebagai bukti.
Pasukan keamanan menghadang aksi jalan kaki mahasiswa. Terjadi bentrok, pasukan menyerbu kampus. Mahasiswa kocar-kacir. Radio Australia dan BBC seksi Indonesia gencar sekali memberitakanya. Isu beredar, sejumlah mahasiswa tewas dalam insiden itu.
Sebelumnya, terjadi insiden Remexio, nama kota kecil sekitar 30 kilometer selatan Dili. Dua orang tentara berpangkat prajurit dituduh menodai Hosti, lambang penting gereja Katolik di sana. Hosti dalam tradisi Katolik merupakan wujud tubuh Yesus Kristus.
Wakil Gubernur Timor Timur, Brigjen Johannes Haribowo, seorang anggota Kopassus, memanggil saya dan Agus Ismunarno redaktur pelaksana STT ke rumahnya.
“Anda sudah dengar peristiwa yang terjadi di Remexio?” tanya Haribowo. Kami mengangguk. “Ini gawat,” katanya lagi. “Saya sudah bilang pada Pak Lumintang bahwa lebih baik kita membakar katedral Dili daripada menginjak-injak lambang religi paling penting ini,” ujarnya.
Haribowo seorang pemeluk Katolik. Dia tahu apa yang bakal terjadi di luar perkiraan. Haribowo minta agar STT jangan dulu memuat insiden ini. Lumintang yang dimaksudnya adalah Kolonel Johny Lumintang, saat itu komandan Komando Resor Militer Timor Timur.
STT tidak dengan serta-merta mengikuti saran Haribowo. Saya dan Peter Tukan, seorang wartawan STT, menemui Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo di rumahnya. Uskup sudah mendengar apa yang terjadi di Remexio, tapi dia belum yakin benar apa yang sebenarnya terrjadi. Begitu pun STT. Tidak ada wartawan yang hadir ketika peristiwa terjadi. Kami menanyai sejumlah saksi mata dan menurunkannya dalam berita kecil dan ditulis samar-samar. Hari berikutnya kami memuat seruan Uskup Belo agar warga Timor Timur tidak menaruh amarah terhadap apa yang terjadi. Uskup Belo meminta semua warga Timor Timur untuk berdoa memohon perdamaian.
Selesai kasus Remexio. Meledak insiden Universitas Timor Timur. Situasi Dili genting. Ribuan pemuda bersiap-siap membantu mahasiswa. Penguasa militer Dili meminta STT menulis berita dari sumber kepolisian. Hari pertama aksi, ketika insiden pecah, STT memuat versi polisi. Hari kedua STT diundang di kantor kepala wilayah kepolisian Timor Timur. Ismunarno dan saya yang datang. Di sana sudah menunggu Haribowo, sejumlah perwira menengah angkatan darat, kepala wilayah kepolisian, dan sejumlah koresponden media.
Pertemuan dipimpin Haribowo. Ada Johny Lumintang, ada sejumlah komandan sektor, Komandan Satuan Tugas Penerangan (Satgaspen) Korem Timor Timur, Mayor Laedan Simbolon, dan komandan Satuan Tugas Intelijen Kopassus, Kolonel Sugiarto. Berita STT hari itu dipuji-puji oleh mereka yang hadir. Haribowo membandingkannya dengan berita untuk peristiwa yang sama yang ditulis harian Pos Kupang yang ada di tangannya. Pos Kupang, salah satu anggota jaringan media daerah milik Kelompok Kompas Gramedia, yang terbit di Kupang. Jadi masih saudara dengan STT. Pos Kupang menulis dengan judul “Bentrokan di Dili, Tiga Mahasiswa Tewas.” Edisi hari yang sama untuk peristiwa itu, STT menulis berita berjudul “Kapolwil Timtim: Tidak Ada Korban Tewas.” Ada yang tak diketahui para tentara itu, kecuali Mayor Simbolon yang hanya bisa berungut-sungut, bahwa berita yang dimuat Pos Kupang sebenarnya berita STT yang tidak bisa dimuat.
Setelah berbasa-basi sebentar, mendengarkan laporan singkat para komandan lapangan, Haribowo memandangi kami berdua. Dia berkata, “Sekarang, apa headline STT besok pagi?” Saya terperanjat, Ismunarno tersenyum tapi tak segera menjawab. Wartawan-wartawan yang hadir terdiam. “Pak Haribowo,” kata saya. Semua mata segera tertuju ke saya. “Begini, kami tidak bisa memberitahu apa berita yang akan kami tulis besok. Ini sama dengan kalau kita bertanya kepada Pak Sugiarto, ‘Pak, siapa besok yang akan ditangkap’?”
Semua tertawa, suasana cair. Kolonel Sugiarto komandan Satuan Tugas Intelijen Kopassus atau biasa disebut SGI. Satuan ini dikenal suka main tangkap orang. Sugiarto juga tertawa. Ini pertama kali saya melihatnya tertawa. Perwira ini berwajah angker. Mengingatkan pada raut wajah Jenderal Benny Moerdani, salah satu pembantu Presiden Soeharto, yang pernah jadi menteri pertahanan. Esok harinya, kami tetap tak berani menurunkan berita versi sendiri.
Dua berita yang dimuat STT tentang peristiwa itu memperoleh protes dari Universitas Timor Timur. Pastor Broto Wiyono S.J., sang rektor menelepon. “STT berat sebelah. Kami punya versi tentang peristiwa itu. Apakah bisa disiarkan?” tanya Romo Broto.
Saya maupun Ismunarno cukup dekat dengan Romo Broto. Pastor setengah umur ini mantan dosen Ismunarno di Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Sanata Dharma, Yogyakarta. Romo Broto sangat dihormati para mahasiswanya. Ketika kampus dikepung selama tiga hari, dialah orang yang berdiri di depan gerbang bernegosiasi dengan komandan militer dan polisi agar tidak menyerbu kampus. Dia juga yang membujuk penguasa keamanan Dili agar membebaskan belasan mahasiswanya yang ditangkap dengan imbalan penghentian aksi mahasiswa di kampus.
Saya satu-satunya wartawan yang bisa masuk ke kampus. Pasukan keamanan membiarkan saya melewati pagar betis dan para mahasiswa membiarkan saya berada di tengah-tengah mereka. Di sebuah ruang kelas, sejumlah mahasiswa terluka. Tidak ada paramedis di sana, hanya seorang pria dari palang merah internasional berkebangsaan Swiss. Dia kewalahan dan membujuk mahasiswa agar membawa para korban ke rumah sakit. Namun, para mahasiswa menolak. Pergi ke rumah sakit sama artinya menyerahkan diri hidup-hidup ke pasukan Indonesia. Tentara menawarkan paramedis untuk merawat para mahasiswa yang terluka namun jasa baik ini ditolak.
Kami mengundang Romo Broto ke kantor, berdiskusi panjang lebar tentang kesulitan dengan pihak militer yang kami hadapi. Romo Broto orang yang enak diajak bicara, penuh humor, dan tidak gampang marah. Dia bisa mengerti situasi sulit yang kami hadapi. Lalu, kami memberi saran agar universitas membuat konferensi pers perihal insiden tiga hari di kampus itu dari sudut pandang universitas. Dari sanalah STT bisa bersiasat memuat versi universitas. Romo Broto setuju.
Kami memuat hasil konferensi pers itu dan memuat kronologi kejadian versi universitas. Pemuatan ini memancing kemarahan militer Indonesia. Seorang perwira penerangan menelepon. Kami menjawab kemarahan itu dengan sebuah kalimat, “Universitas menggunakan hak jawabnya yang selama pemberitaan tentang insiden kami diabaikan.” Johannes Haribowo mencari-cari saya dan Ismunarno. Kami menghilang beberapa saat.
PEMERINTAH Belanda memutuskan akan menutup Radio Hilversum seksi Indonesia. Joss Wibisono, seorang penyiar Radio Hilversum, mencari dukungan ke Jakarta. Yosep Adi Prasetyo dari majalah Jakarta-Jakarta yang dikontak Joss, meminta bantuan kami di Dili untuk memberikan protes ke pemerintah Belanda atas rencana penutupan itu.
Saya segera menyusun nota protes yang berisi permintaan agar Radio Hilversum tetap mengudara. “Di Indonesia, media tidak bebas. Radio asing berbahasa Indonesia sangat menolong bagi penyebaran informasi yang benar. Bagaimanapun, Radio Hilversum memiliki peran yang besar menyiarkan fakta-fakta pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur.” Ini kutipan nota protes itu. Uskup Belo membubuhkan tanda tangan paling atas, menyusul belasan wartawan STT.
Nota dibawa seorang kawan yang kebetulan akan berangkat ke Jakarta yang kemudian dilanjutkan ke pemerintah Belanda. “Berkat pernyataan dari Dili, pemerintah Belanda mengurungkan niat menutup radio kami,” ujar Joss Wibisono di kemudian hari.
Radio asing berbahasa Indonesia di Timor Timur merupakan medium yang sangat diminati. Hampir semua orang dewasa mendengarkan siaran dari ABC, BBC, dan Radio Hilversum, tiga stasiun radio asing yang sangat dikenal.
Dili pukul 8.00 sudah menjadi kota mati. Jalan-jalan sepi. Sesekali truk penuh tentara bersenjata api melintasi jalan. Atau serombongan orang berambut cepak berpakaian sipil jalan-jalan dengan menenteng senapan serbu M-16. Toko-toko sudah tutup dan warga kota mengunci diri di rumah mereka. Saat itulah mereka menguping siaran radio asing.
James Lapian dari BBC seksi Indonesia beberapa kali mewawancarai saya melalui telepon. Tanggal 17 Juli 1994, Lapian meminta saya melaporkan situasi Dili saat Hari Integrasi. BBC juga meminta saya menceritakan situasi Dili ketika terjadi pertikaian antara massa prointegrasi dan massa prokemerdekaan pada 1994 dan waktu peringatan peristiwa Santa Cruz, November 1995. Radio asing, terutama yang menyiarkan berita tentang Timor Timur, selalu dimonitor militer. Ketika BBC pertama kali menyiarkan wawancara saya, intelijen militer mengorek keterangan tentang saya dari kawan-kawan STT.
Radio ABC juga rajin menelepon. Radio Portugal hanya sesekali. Biasanya langsung langsung diterima Jose Xinenes, satu-satunya wartawan STT yang bisa berbahasa Portugis. Layaknya media di tempat jauh, STT memang jadi semacam rujukan atau clearing house bagi orang luar untuk mencari tahu soal Timor Timur. Tidak hanya wartawan Jakarta atau asing, namun juga para diplomat kedutaan asing di Jakarta. Pejabat kedutaan Australia yang paling sering berkunjung ke kantor kami. Mereka sering mampir dan bertanya banyak hal. Orang-orang kedutaan Amerika, Inggris, Jepang, dan Norwegia juga acap mampir.
Duta besar kita dari luar negeri juga kadang mampir. Suatu hari kami kedatangan tamu, seorang duta besar yang dulunya redaktur harian The Jakarta Post, Sabam Siagian. Ketika itu dia duta besar untuk Australia. Siagian, seperti lazimnya para pejabat Indonesia yang mampir ke kantor kami, menegur dengan gayanya yang agak keras.
Wartawan asing koresponden Far Eastern Economic Review di Jakarta, Margot Cohen, sesekali menelepon. Misalnya 20 Mei 1994, Cohen menelepon saya, menanyakan situasi di Dili menjelang konferensi Asia Pasifik tentang Timor Timur di Manila.
Situasi Dili menjelang konferensi Manila menghangat. Selama berhari-hari saya menulis tajuk berisi dukungan penyelenggaraan konferensi itu bagi penyelesaian damai masalah Timor Timur. Di Jakarta, Menteri Luar Negeri Ali Alatas mati-matian berusaha menggagalkannya, antara lain dengan menekan Manila. Hasilnya, Jose Ramos-Horta, tokoh kemerdekaan Timor Timur, dilarang masuk ke Filipina. Tajuk-tajuk STT rupanya dibaca banyak orang, termasuk para perwira militer di Dili. Mayor Laedan Simbolon dari Satuan Tugas Penerangan Korem menegur.
Teguran itu tidak menyurutkan STT. Berita tentang konferensi ini sangat dinanti-nantikan pembaca. Saya mewawancarai Uskup Belo untuk memperkaya berita ini. Uskup Belo mendukung konferensi itu. Wawancara ini dimuat di berita utama pada 24 Mei 1994. Tidak ada teguran dari militer. Saya lega.
LETNAN Situmorang melompat dari mobilnya menerobos masuk ke ruang tamu kantor redaksi. Waktu itu, Juni 1994, hari masih pagi. Kami baru saja menyudahi rapat. “Komandan ingin bertemu. Ada berita yang tidak benar,” ujarnya. Situmorang perwira dari Dinas Penerangan Angkatan Darat yang diperbantukan ke Korem Timor Timur. Dia dikirim Mayor Simbolon untuk menjemput redaktur STT. Ismunarno sedang berada di Yogyakarta. Redaktur paling senior adalah Mohamad Yamin, redaktur harian Sriwijaya Post, Palembang, yang diperbantukan di tempat kami. Sriwijaya Post juga salah satu jaringan koran daerah milik Kelompok Kompas Gramedia. Redaktur senior lainnya ya saya.
Situmorang meminta kami berdua ikut ke mobilnya, sebuah land rover hijau milik Angkatan Darat. Di pintu keluar, saya menitip pesan kepada kawan-kawan yang hanya bisa memandangi, agar berbuat sesuatu jika hingga malam nanti kami belum pulang.
Penjemputan ini menyangkut sebuah berita yang dimuat saat itu tentang penganiayan kepala sekolah menengah di Natarbora oleh beberapa tentara. Natarbora merupakan kota kecamatan terpencil di pantai selatan Timor Timur. Berita ini kontan memancing kemarahan para perwira Korem.
Tiba di markas Satgaspen, Mayor Simbolon sudah menunggu. “Kalian bisa dipenjara! Ini daerah operasi militer!” Simbolon membentak, mengucapkan kalimat itu berulang-ulang. Di ruang kerjanya ada beberapa korensponden koran Surabaya dan wartawan Antara biro Dili. Melihat gelagat yang kurang baik, mereka segera pamit. Simbolon membawa kami ke markas Korem.
Kami ditempatkan di sebuah ruang yang tidak terlalu luas, ada seperangkat sofa sudut. Seperangkat radio komunikasi berada di pojok ruangan. Suara radio itu amat keras bersahut-sahutan. Para operator radio itu rupanya tengah menginformasikan kehadiran kami di Korem.
“Dua walet sudah datang, diantar Mayor Simbolon,” demikian potongan dialog yang masih saya ingat. Walet, saya duga, adalah nama sandi untuk wartawan. Jadi, penjemputan kami sudah diketahui hampir semua operator radio komunikasi militer.
Perwira berpangkat letnan kolonel yang saya kenali sebagai kepala seksi teritorial Korem, menghardik kami. “Ini ya, wartawan yang nulis itu. Kalau saya komandan batalionnya, saya bunuh kalian!” Hardikan itu agak menjatuhkan mental. Wajah perwira itu, dengan kumis yang dipelihara dan dirawat, memerah. Lalu, dia berlalu. Simbolon membawa dua gelas air mineral untuk kami. Saya meneguknya hingga tandas. Sejak pagi saya belum minum setetes air pun, apalagi sarapan.
Kami diminta menunggu. Komandan Korem Kolonel Lumintang ingin bertemu. Ternyata, sang kolonel masih berada di Baucau, dibutuhkan waktu sekitar satu jam perjalanan dengan helikopter untuk sampai di Dili. Namun, hingga tengah hari, kolonel yang ditunggu-tunggu belum kembali. Terompet tanda waktu ditiup petugas jaga. Suaranya mirip lolongan anjing.
Seorang pewira berpangkat kapten masuk ruangan. Saya paham tanda-tanda pangkat militer karena ayah saya seorang tentara. Saya juga menghabiskan masa remaja di kompleks tentara. Lelaki ini cukup tampan, berkulit putih, tidak berkumis, dan ramah. Dia tidak pernah menghardik. Menyapa kami dengan sopan dan mengajak diskusi tentang banyak hal tanpa menyinggung sedikit pun berita yang dipersoalkan itu. Perwira muda ini tampaknya berpendidikan luar negeri, sebab di lengan kanannya menempel tanda Airborne. Kehadiran perwira ini melegakan, setidaknya tidak semua perwira yang menemui kami galak dan kasar.
Hingga sore hari, kami menunggu Lumintang. Perut saya keroncongan. Simbolon tidak menyediakan makan siang. Kami juga tidak berani memintanya. Apalagi minta izin makan siang di luar. Tak ada lagi tambahan air mineral. Pukul lima sore, ada jemputan dari kantor. Dua orang wartawan STT rupanya berupaya mencari tahu tentang nasib kami. Simbolon memutuskan melepas kami dan akan menjemput esok harinya untuk ketemu Lumintang. Kami langsung makan di warung nasi milik orang Lamongan di seberang rumah kos saya di bilangan Kolmera, tak jauh dari markas SGI.
Esoknya, pagi hari, kami dijemput lagi, diantar ke Markas Korem. Letnan Kolonel Budiatmo, kepala seksi intelijen Korem yang menemui kami. Sekarang, kami dijemput bertiga, Yamin, Yesayas Petruz , reporter yang menulis berita tersebut, dan saya. Ruang kerja Budiatmo tidak terlalu luas. Kami bertiga dan Mayor Simbolon duduk mengerumuni meja kerja si perwira. Simbolon memperkenalkan kami. Budiatmo bilang berita itu tidak benar, tidak ada peristiwa penganiayaan. Dia menanyakan sumber berita kami.
Berita itu memang tidak lengkap. Yamin yang mengeditnya mengakuinya dalam rapat redaksi. Informasi tentang penganiayaan itu datang dari tiga penduduk Natarbora yang melaporkannya ke kantor STT. Kantor kami, selain sebagai kantor suratkabar, juga seringkali terasa bagai kantor lembaga bantuan hukum. Banyak orang datang mengeluhkan anaknya yang hilang, terbunuh, atau ditahan.
Yesayas Petruz, reporter asal Pulau Kisar, Maluku Tenggara, menerima informasi itu. Dia menulisnya tanpa mengecek lebih dulu dan tanpa wawancara dari pejabat militer yang bisa dikontak di Dili. Berita itu juga tidak dilengkapi dengan wawancara korban, elemen yang sangat penting dalam pemberitaan kasus semacam itu. Di rapat redaksi berita itu diputuskan untuk dicabut.
Kami bilang pada Budiatmo bahwa redaksi sudah mencabut berita itu. Budiatmo tampak tidak puas. Namun, pembicaraan terputus karena telepon berdering. Budiatmo mengangkatnya, berbincang sejenak kemudian menutup telepon. “Apakah Mochtar Lubis itu anggota Petisi 50?” tanyanya. Dia rupanya baru saja memperoleh informasi bahwa wartawan kawakan dari Indonesia Raya itu ada di Dili.
Mochtar Lubis diundang Universitas Timor Timur untuk bicara mengenai buku riwayat perjuangan Nelson Mandela, tokoh pembebasan Afrika Selatan yang baru saja diterbitkan Yayasan Obor. Kebetulan Lubis ketua yayasan itu. Kami sudah mengetahui kedatangannya. Dan, hari itu kami menukil buku itu di halaman muka koran kami. Diskusi buku itu jelas sebuah simbol. Hal yang dengan gampang diketahui maksudnya.
Budiatmo rupanya tidak kenal siapa Mochtar Lubis. Saya maklum. Saya menjelaskan agak panjang lebar tentang siapa Lubis. “Ia bukan anggota Petisi 50,” ujar saya. Budiatmo manggut-manggut. Dia agak lega mengetahuinya. Para penandatangan Petisi 50, di zaman itu merupakan musuh Presiden Soeharto nomor satu. Budiatmo bukan perwira yang kasar, dia agak mengancam tapi tidak terlalu menakutkan. Kami boleh pulang setelah dia memberi nasehat panjang lebar.
Namun urusan belum selesai. Keluar dari ruang kerja Budiatmo, markas SGI sudah melayangkan panggilan. Kami diminta datang ke markas satuan tugas Kopassus. Di sana kami diminta menemui Kolonel Sugiarto yang angker itu. Di teras markas itu, sejumlah anggota SGI, semuanya berpakaian preman, sedang bermain karambol.
Sugiarto menemui kami di dekat meja karambol. Saya bilang kepadanya bahwa masalah ini sudah diselesaikan di Korem, jadi STT tidak punya masalah lagi dengan tentara, apalagi dengan SGI. Kolonel itu tidak menjawab. Di sekitar meja karambol sudah ada seorang pria kurus yang mengaku sebagai kepala sekolah menengah di Natarbora yang diberitakan dianiaya itu dan dia segar bugar. Saya tidak segera percaya. Saya meminta kartu identitasnya. Permintaan ditolak.Tak lama kemudian kami diperbolehkan pulang dengan pesan sewaktu-waktu akan dipanggil lagi. Di kantor, saya mengetahui Budiatmo memanggil empat atau lima reporter untuk menghadap esok harinya. Saya agak marah dan meminta kawan-kawan untuk tidak mematuhi panggilan itu.
Rapat sore memutuskan esok hari STT mogok terbit. Keputusan itu dilaporkan ke Jakarta. Ditujukan kepada Valens Doy, pemimpin redaksi STT yang lebih banyak tinggal di Jakarta. Doy menulis surat yang dikirim melalui modem. “Saya menghargai keputusan kalian untuk tidak terbit sebagai protes atas tindakan militer. Namun, sebaiknya niat itu diurungkan,” demikian kurang lebih kutipan surat Valens. Mogok terbit dibatalkan.
Kawan-kawan memenuhi panggilan itu. Mohamad Yamin, Setyo MR, manajer produksi STT, dan saya, diminta menemui wakil komandan Korem, Kolonel Kiki Sjahnakri. Pria ini cukup tampan, gagah dengan seragam tentara, namun kumisnya yang tebal membuat wajahnya angker. Ruang kerja Sjahnakri cukup luas, lantainya berkarpet, dan pendingin ruangan bekerja dengan baik. Sofanya empuk.
Sjahnakri tidak banyak bicara. Dia membuka percakapan dengan bertanya, “Apa menurut Anda arti kebebasan pers yang bertanggung jawab?” Bagi saya ini pertanyaan retorik, pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Kami bertiga, secara bergiliran, wajib menjawab. Sjahnakri kemudian memberi briefing singkat. “Anda tahu berapa prajurit kita yang tewas di sini? Limabelas ribu,” katanya. Saya tahu ke mana arah pembicaraan Sjahnakri. Kira-kira setengah jam kemudian kami diperbolehkan pulang. Sjahnakri kini berpangkat letnan jenderal dan menduduki posisi penting sebagai wakil kepala Angkatan Darat. Dulu, setelah tidak lagi bertugas di Timor Timur, dia selalu mengirim kartu ucapan ke redaksi STT, setiap Natal tiba.
XANANA Gusmão sosok yang dicintai, selain Uskup Dili Carlos Filipe Ximenes Belo. Dia tokoh pembebasan nasional, berpenampilan mirip Ernesto “Che” Guevara, pejuang revolusi dari Kuba. Para pedagang di Mercado Municipal selalu menyisihkan uang untuk membeli koran STT, setiap kali Gusmão muncul di koran kami. Berita tentang Gusmão, apapun itu, selalu kami taruh di halaman satu dan selalu menjadi berita utama. Berita tentang Gusmão dirindukan orang-orang Timor. Koran kami selalu terjual habis jika nama Gusmão muncul. Oplah selalu ditambah. Bagi STT Gusmão adalah berkah.
Gusmão ditangkap di Balide, Dili di rumah seorang sersan polisi oleh pasukan Kopassus yang dipimpin Kolonel Mahidin Simbolon. Pengadilannya pada Februari 1993 menjadi berita utama STT hampir setiap hari. Pengadilan itu berkah bagi STT. Oplahnya naik hingga 10 ribu eksemplar. Rekor yang belum pernah tertandingi. Untuk mempromosikan koran, spanduk-spanduk berisi iklan berita tentang Gusmão di pasang di sudut-sudut kota. Tentara tidak senang. Mereka kemudian menurunkan spanduk-spanduk itu. Tapi koran tetap laku.
Jose Ramos-Horta tidak setenar Gusmão. Mungkin karena Ramos-Horta berjuang di luar negeri dan jarang kontak dengan rakyat Timor Timur. Sosok pemimpin pejuang bersenjata seperti Gusmão, biasanya lebih dikenal rakyat ketimbang sosok politisi seperti Ramos-Horta. Seperti revolusi Kuba, Manuel Urrutia, sosok politisi pemberontak, tidak lebih dipuja-puja ketimbang Che Guevara dan Fidel Castro, dua pentolan gerilyawan, ketika mereka semua bahu-membahu menumbangkan rezim Baptista, Januari 1959. Di aksi-aksi prokemerdekaan, yang sering saya saksikan di Dili, gambar Ramos-Horta tidak pernah diangkat para demonstran, melainkan “Viva Xanana.”
Gusmão bernama asli José Alexandre Gusmão, seorang terpelajar yang pernah mengenyam pendidikan di seminari Jesuit, sekolah calon pastor Katolik. dia juga seorang penyair dan sedikit punya keahlian melukis. Pada 1974, sajaknya berjudul Mauberedias memenangkan lomba puisi di Timor Portugis. Sebuah sajak yang menyentuh. Sajak itu, terilhami epik Lusiads, karya penulis besar Portugis, Luis De Camoes.
Xanana adalah nama samaran Gusmão untuk sejumlah tulisan dan sajaknya yang sering dimuat Avos de Timor, koran mingguan di zaman Timor Portugis yang diterbitkan Jose Ramos-Horta. Avos de Timor artinya Suara Timor. Koran itu berbahasa Portugis, digunakan untuk menyampaikan ide-ide kemerdekaan. Xanana artinya nanas.
Ramos-Horta memang tidak bisa dibandingkan dengan Gusmão. Di luar negeri, Ramos-Horta lebih dikenal daripada Gusmão. Hadiah Nobel Perdamaian jatuh ke tangannya bukan Gusmão. Ramos-Horta juga sangat rajin dan ulet. “Ia hanya tidur selama empat jam sehari,” ujar Arief Budiman, profesor Universitas Melbourne, Australia, yang kagum terhadap semangat Ramos-Horta, “Dia mengetuk dari pintu ke pintu mengkampanyekan kemerdekaan Timor Timur.”
Pengganti Gusmão setelah dia ditangkap adalah seorang gerilyawan bernama Antonio Gomes da Costa atau dikenal sebagai Mauhunu. Dia memegang kendali Forcas Armadas da Libertacao Nacional de Timor Leste atau kalau diterjemahkan artinya tentara pembebasan nasional Timor Timur dan biasa disingkat Falintil. Namun, tak lama, Mauhunu ditangkap pasukan Kopassus. Bersamanya ditangkap pula seorang pemimpin gerilayawan lainnya Jose da Costa alias Mauhudu.
Tidak seperti Gusmão, kedua pria ini tidak diadili. Mereka “diampuni”. Mauhunu tinggal di markas intelijen Kopassus dan Mauhudu diperbolehkan bekerja di kantor pemerintah. Ke mana-mana, Mauhunu dikawal para petugas Kopassus dengan sebuah mobil Kijang. Saya sering bertemu, secara tidak sengaja, di jalan atau di pekuburan Santa Cruz ketika kami sama-sama melayat. Dari matanya saya bisa merasakan betapa pejuang ini merasa terpenjara kendati bebas ke mana-mana dengan pengawalan. Jika berpapasan di lampu merah misalnya, dia seringkali menoleh dan melemparkan senyum kecil. Bagi pejuang seperti Mauhunu, tinggal di markas musuh, kendati tidak diperlakukan seperti tawanan, akan membuat hatinya hancur. Dia tidak tinggal di sel. Namun, di markas itu, dia menyaksikan kawan-kawan seperjuangannya “digarap.”
Markas itu tidak terlalu luas. Beberapa kali saya berkunjung ke sana atas undangan Kolonel Sugiarto. Suatu hari, kami berusaha melakukan cross check tentang khabar bahwa sejumlah pemuda ditangkap secara sewenang-wenang oleh petugas militer. Saya dan Ismunarno diminta datang ke markas itu, lalu oleh sang kolonel sendiri, kami diajak menyaksikan sel-sel tahanan di markas itu, untuk membuktikan, tentara tidak menangkap mereka. Di markas itu, selain Mauhunu, juga tinggal Luis Akuiliong, sopir truk yang bertugas menyelundupkan Gusmão dari hutan ke Dili. Dia juga berada dalam pengawasan Kopassus.
Di Timor Timur, selain Gusmão, simbol lain adalah Uskup Belo. Saya merasa takjub jika diajaknya berkunjung ke daerah. Orang-orang di pinggir jalan di desa-desa yang dilalui biasanya berlutut jika mereka melihat mobil Uskup Belo melintas. Orang-orang mencium tangannya dan saya selalu diperkenalkannya sebagai wartawan. Selain saya, biasanya Uskup Belo juga mengajak Peter Tukan, kawan saya di STT. Tukan yang memperkenalkan saya dengan Uskup Belo.
Uskup Belo berpribadi hangat. Dia mengenal saya sejak George Junus Aditjondro, dosen saya di Salatiga, yang menaruh minat besar pada Timor Timur, menitipkan dua naskah bukunya, Dari Memo ke Tutuala dan Under the Shadow of Mount Ramelau, untuk saya berikan pada Uskup Belo. Aditjondro bertemu Uskup Belo di bandara El Tari, Kupang, Mei 1994. Uskup Belo dicap sebagai musuh integrasi nomor satu oleh penguasa Indonesia. Uskup Belo pernah bilang pada saya bahwa tuduhan itu keliru. Gereja tidak berpolitik. “Gereja Katolik berada di atas semua aliran politik di sini,” ujarnya.
MOBIL Toyota Kijang milik STT dibakar pada suatu malam. Peristiwanya berlangsung amat cepat. Mobil itu diparkir di halaman kantor. Seorang penyusup rupanya mengendap-endap, menyiramkan bensin ke jok mobil, membakarnya, lalu kabur. Kami berusaha keras memadamkan api. Ini mobil kami satu-satunya. Jasanya cukup besar. Tiap pagi, dengan mobil ini kami membagi koran ke agen-agen di seluruh Dili. Mobil itu harus diperbaiki. Butuh uang yang cukup banyak.
Sulit menebak, siapa yang melakukannya. Esok harinya STT terbit dengan berita utama pembakaran mobil itu. Foto rongsokan mobil dimuat. Berita itu sarat opini yang mengaitkan pembakaran itu dengan pemberitaan STT. Kontan, berita itu memancing kemarahan tentara. Kolonel Lumintang mengundang wartawan di sebuah restoran Cina di tengah kota Dili. Dia menolak pendapat STT tentang motif pembakaran. Dia menyumbang Rp 1 juta untuk perbaikan mobil itu.
Pembakaran ini menjadi peristiwa yang paling menekan. Sepanjang terbitnya, sejak Februari 1993, serangan fisik seperti ini belum pernah terjadi. Puluhan orang yang tersinggung dengan berita kami pernah datang menggunakan dua minibus carteran, tapi mereka tidak merusak, apalagi melukai. Satu-dua orang sering datang dan marah-marah, tapi masalah bisa diselesaikan dengan damai. Ancaman pembunuhan lewat telepon juga sering datang, tapi biasanya hanya gertak sambal. Semua menjadi lazim.
Sejak itu kekerasan demi kekerasan terhadap STT terus terjadi. Pada 7 Desember 1995, kantor kami diserbu serombongan pemuda dari sebuah organisasi pemuda propemerintah, yang di zaman Orde Baru sangat ditakuti. Televisi dan video player dirusak. Pada saat yang sama Jakob Herin, wartawan senior Suara Timor Timur dan koresponden The Jakarta Post, diculik orang-orang suruhan Ahmad Alkatiri, ketua organisasi Pemuda Pancasila setempat. Ahmad Alkatiri adalah adik kandung Mar’ie Alkatiri, salah satu tokoh pembebasan Timor Timur di luar negeri. Herin diculik karena dihubungkan dengan berita yang ditulisnya di STT mengenai upaya pembunuhan terhadap Ahmad Alkatiri. Herin dijemput dengan mobil milik anggota tentara. Di rumah Ahmad Alkatiri, Herin dipukul beberapa kali. Kasihan dia.
Saya ketika itu sedang berada di Jakarta. Di gedung parlemen Senayan, Jakarta, kebetulan Menteri Penerangan Harmoko sedang rapat dengar pendapat di parlemen. Kesempatan itu saya gunakan untuk memunculkan kasus ini. Bersama Jose Ximenes, wartawan STT yang tengah mengikuti pendidikan jurnalistik di Jakarta, saya mencegatnya. Harmoko mengecamnya sebagai penyerangan. Kecaman Harmoko dimuat sejumlah media massa. Malamnya saya mengadukan penyerangan ini ke Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di kantor mereka di Tanah Abang, Jakarta.
Saya bertemu Eko Maryadi, Danang Kukuh Wardoyo, dua aktivis AJI yang kemudian masuk penjara, dan Satrio Arismunandar, ketika itu wartawan Kompas, sebelum dipaksa mundur dari koran ini karena mendirikan AJI. Penyerangan itu dimuat majalah Independen, majalah bawah tanah yang dikelola anak-anak AJI. Ahmad Alkatiri akhirnya mengirim permintaan maaf berupa iklan di harian Kompas. Barang-barang yang dirusak diganti. Herin juga tidak mengajukan tuntutan kendati apa yang dilakukan Alkatiri kepada wartawan setengah umur itu merupakan kejahatan yang berat.
Beberapa bulan kemudian, Ruhut Sitompul, salah seorang pengurus pusat Pemuda Pancasila, mengunjungi kantor kami di Dili. Saya menemuinya. Dia bilang, apa yang terjadi hanya “kesalahpahaman.”
Herin bagi saya seorang jurnalis yang pantas dihormati. Dia tidak berpendidikan tinggi. Lahir di Flores, dan bukan orang Timor. Kemampuan menulisnya pas-pasan. Saya selalu melakukan tulis ulang jika menemukan beritanya masuk ke desk saya. Namun, daya tembusnya luar biasa. Dia tidak hanya mampu menembus sumber militer untuk berita yang amat sensitif sekalipun, dia juga bisa hadir di sebuah rapat penting gerakan bawah tanah prokemerdekaan. Sekitar Juli 1995, Herin ditugaskan meliput berita tentang persiapan para aktivis prokemerdekaan di Dili “menyambut” kedatangan pelapor khusus Persatuan Bangsa Bangsa, Alaya Lasso. Herin berhasil hadir dalam rapat-rapat mereka.
Lasso disambut dengan demonstrasi. Setelah itu, penangkapan dilakukan terhadap para demonstran. Ada interogasi, sebagian dari yang ditangkap menyebut nama Herin sebagai bagian dari mereka. Herin diintai, dia kami minta tidur di kantor. Suatu subuh, sebuah mobil sewaan membawanya ke Timor Barat. Dia berhasil tiba di Kupang dengan selamat, lalu menyeberang ke tanah kelahirannya Flores. Sejak itu, dia tidak pernah kembali ke Dili.
MATA saya berkaca-kaca. Pesawat sudah menunggu di landasan ketika saya boarding di bandar udara Komoro, Dili. Waktu itu, 16 Agustus 1994, beberapa kawan dari STT, mengantar kepergian saya. Mereka tampak sedih. Saya mesti pulang sebelum waktunya.
Dua hari sebelumnya, Salvador Soares, pemimpin umum STT, memberitahukan bahwa penguasa militer meminta saya meninggalkan Timor Timur. Valens Doy, pemimpin redaksi STT, yang membawa kabar itu. Doy mantan redaktur senior Kompas. Dia diminta orang nomor satu Kompas, Jakob Oetama, memimpin STT. Tapi Doy lebih banyak berada di Jakarta. Dou jarang datang ke Dili. Sehari-hari STT dipimpin Agus Ismunarno, wartawan dari divisi pers daerah Kelompok Kompas Gramedia. Jabatan Ismunarno redaktur pelaksana.
Yayasan Tatoli Naroman, penerbit STT, menjalin kerjasama dengan Kelompok Kompas Gramedia. Namun Kompas sama sekali tidak memiliki saham di harian itu, kendati memberi bantuan manajemen redaksi, bisnis dan pasokan berita dari Jakarta.
Valens Doy khusus datang ke Dili untuk urusan “deportasi” saya. Pertama kali yang diajaknya bicara Salvador Ximenes Soares, pemimpin redaksi STT merangkap anggota parlemen, yang juga serign berada di Jakarta.Valens Doy sama sekali tidak pernah berbicara dengan saya soal pengusiran ini. “Valens meminta saya untuk melakukan sesuatu yang tidak saya sukai,” ujar Salvador, di lobi sebuah hotel, tak jauh dari rumah Uskup Belo. Saya tidak bertanya lebih jauh dan Salvador Soares tidak berkata apa-apa lagi. Esoknya, dia baru memberitahu saya bahwa Valens Doy diminta Jakob Oetama untuk menjemput saya. “Jakob ditelepon seorang jenderal dari Mabes ABRI. Jenderal itu minta agar kamu meninggalkan Dili secepat mungkin” ujar Salvaldor. Dia menyebut nama seorang letnan jendreal. Apa boleh buat. Tiket pesawat sudah dipesan. “Kamu harus pergi dalam dua hari. Selebihnya mereka akan tangkap,” Salvador menambahkan.
Tapi apa salah saya? Salvador tak bisa menjawab, tidak juga Valens. Perintah “deportasi” yang diterima Valens juga tidak menyertakan alasan.
GIL ALVES datang pukul dua sore [kapan ini?]. Wajahnya tampak tegang. Saya menemuinya di lobi redaksi. Alves adik ipar gubernur Abilio Soares. Dia kontraktor yang cukup sukses di bekas jajahan Portugis itu. “Kamu harus cepat-cepat meninggalkan Timor Timur,” ujarnya.
Alves baru saja menghadiri jamuan makan siang untuk Kolonel Prabowo Subianto di rumah jabatan gubernur. Di Prabowo sering mengunjungi Timor Timur. Dia amat dekat dengan keluarga Abilio Soares.
Dari acara makan siang itulah Gil Alves memperoleh informasi tentang rencana pengusiran saya. “Mereka tidak main-main,” ujar Alves lagi. Saya mengenal Gil Alves beberapa bulan setelah saya tiba di Dili. Saya berkawan dengan siapa saja, tidak hanya dengan orang-orang prointegrasi, tapi juga dengan orang-orang prokemerdekaan. Sebagai wartawan saya tidak boleh partisan, menolak bergaul dengan orang-orang prointegrasi atau sebaliknya. Saya dekat dengan anak-anak di Yayasan Etadep, yang sebagian aktivisnya kemudian mendirikan Yayasan Hak yang bergerak di bidang hak asasi manusia.
Informasi Alves sangat berharga bagi saya. Di rapat sore yang dipimpin Valens Doy, saya mengutarakan hal ini. Rapat sore itu sebenarnya tengah membahas soal saling tuduh sebagai informan militer di redaksi. Sejumlah kawan menuding dua wartawan STT menjual informasi kepada militer. Debatnya panas sekali. Wartawan yang dituding intel tak terima, sementara sekelompok wartawan lainnya membeberkan bukti-bukti. Saya sendiri enggan terlibat dalam tuding-menuding itu. Valens Doy yang akhirnya menengahi.
Doy tak bereaksi, ketika saya menceritakan informasi yang saya peroleh. Saya menolak pengusiran ini. Doy tidak bereaksi, namun saya melihat dari wajahnya, dia tidak suka dengan cara saya berbicara. Setelah rapat, Salvador meminta saya untuk menerima saja. Saya tidak punya pilihan lain. Tiket pesawat sudah dipesan dan saya berkemas-kemas. Hingga tiba di Jakarta, saya tidak tahu mengapa mereka mengusir.
Juni 1995, setelah para komandan dan panglima Kodam diganti, saya pulang ke Dili. Kolonel Mahidin Simbolon sudah jadi komandan Korem. Maret 1996, saya mundur dari STT .
HELIO Freitas tampak kumal. Pakaian, rambut dan wajahnya tak terawat. Kulitnya legam dan kotor. Saya menemuinya di Dili, akhir Mei 2001, lima tahun sesudah saya diusir dari kota ini. Suasana kota itu sangat berubah di bawah kekuasaan Persatuan Bangsa-Bangsa atau tepatnya United Nation Transitional Administration in East Timor (Untaet). Tak ada lagi tentara Indonesia. Banyak orang kulit putih lalu-lalang, juga tentara penjaga perdamaian, dan polisi Untaet berseragam biru-biru.
Helio memimpin sebuah majalah berita Lian Maubere, mingguan nasional berbahasa Indonesia, yang terbit di Dili. Lian Maubere artinya suara rakyat kecil. Seorang pemimpin redaksi mingguan berita di sebuah negeri kecil yang bersiap-siap merdeka, jangan dibayangkan berpenampilan seperti Bambang Harymurti, pemimpin redaksi majalah Tempo dan Koran Tempo, yang berdasi dan rapi. Helio, jauh dari kesan itu. Dia anak seorang petani biasa di Ossu, Viqueque, daerah pegunungan yang dingin. Lulus sekolah menengah atas, dia merantau ke Jakarta, lalu bekerja di Institut Sosial Jakarta.
Pagi-pagi, biasanya dia sudah berada di kantor, sebuah gedung bekas kantor organisasi istri pegawai negeri Indonesia. Ruang redaksinya sangat luas, namun longgar karena hanya ada tiga komputer di sana. Gendung kantor itu milik Untaet, dipinjamkan ke majalah itu dengan pajak US$100 sebulan, jumlah yang sangat besar untuk kantong Lian Maubere yang tiap kali terbit hanya laku 400 dari 1.000 eksemplar yang dicetak. Harga tiap eksemplar US$1, kalau dibeli dengan rupiah Rp 5.000. “Kami bekerja tanpa gaji,” kata Helio.
Lian Maubere mulai terbit Januari 2000, berkat program “padat karya” dari United States Agency for International Development (USAID) –sebuah organisasi bantuan luar negeri milik Amerika Serikat. Di Timor Lorosa’e, USAID membagi-bagikan uang kepada banyak lembaga nonpemerintah dan suratkabar, berupa peralatan dan gaji selama tiga bulan. “USAID mengakui program ini seperti program padat karya di Indonesia untuk menolong pengangguran dalam jangka pendek,” ujar Nugroho Katjasungkana, seorang relawan untuk Yayasan Hak, Dili. Saya sendiri datang kembali ke Timor Timur atas biaya The Asia Foundation, sebuah yayasan Amerika, yang berkantor di Jakarta, yayasan yang meminta saya jadi semacam konsultan media di sana.
Bantuan untuk Lian Maubere, berupa satu unit komputer, dua sepeda motor, dan gaji staf selama tiga bulan. Bantuan lain datang dari negera tetangga, AusAid, lembaga donor pemerintah Australia yang memberi tiga unit komputer dan sebuah sepeda motor. Gaji bantuan USAID hanya bisa dipakai hingga Februari 2000. Sejak bulan berikutnya, para wartawan bekerja tanpa gaji, mengeluarkan uang sendiri untuk biaya peliputan dan overhead. “Uang tabungan saya habis untuk semua ini,” kata Helio.
Kendati menghadapi masalah yang cukup berat, awak Lian Maubere, yang hanya empat orang, tetap bekerja. Hasilnya, majalah itu justru semakin gemuk: terbit setebal 36 halaman. Lian Maubere masih bisa terbit mengandalkan uang hasil penjualan yang hanya cukup untuk ongkos cetak.
Hingga Juni 2001, 17 bulan setelah terbit perdana, majalah ini sudah terbit 19 edisi. Artinya, majalah ini tidak rutin terbitnya. Jika rutin terbit mingguan, seharusnya sedikitnya sudah mencetak majalah 68 edisi. Praktis, majalah ini rata-rata terbit sebulan sekali. “Kami punya masalah keuangan dan tenaga,” ujar Helio.
Rencananya, kantor majalah akan disewakan. Mereka akan pindah ke kantor yang lebih kecil. Ongkos sewa rumah di Dili cukup mahal, sekitar US$1.000 sebulan untuk rumah di tepi jalan besar. Dengan uang sebanyak itu, masalah keuangan bisa diatasi. Lian Maubere jelas bukan majalah yang mapan. Pengetahuan jurnalistik para pengelolanya sangat sedikit. Hampir semua pengelola majalah ini adalah aktivis. Jika hasilnya jauh dari bagus untuk ukuran jurnalistik, harap maklum.
PESAING Lian Maubere, mingguan berbahasa Indonesia bernama Talitakum. Majalah ini dulu buletin bawah tanah yang diterbitkan dari Yogyakarta. Para mahasiswa Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Timor Timur yang mengelolanya. Mahasiswa-mahasiswa itu memboyongnya ke Dili dan jadi mingguan umum. “Kami ingin Talitakum menjadi besar seperti Tempo,” ujar Altide Cassanova dos Santos, pemimpin umum Talitakum.
Talitakum dicetak 1.000 eksemplar dan laku sekitar 800 eksemplar tiap kali terbit. Sayangnya, majalah ini terbit tidak teratur. Akhir Mei lalu, ketika saya mengunjungi kantor majalah ini, mereka baru menyiapkan sebuah edisi yang seharusnya diterbitkan beberapa bulan lalu. Padahal ada 18 orang wartawan. Menurut Altide, adik ipar Mar’ie Alkatiri, menteri perekonomian Untaet, sebagian besar pengelolanya melakukan kerja rangkap. “Kami tak memiliki cukup dana menggaji staf. Sebagian besar tenaga yang ada diperbolehkan mencari pekerjaan tetap di luar,” ujarnya.
Fasilitas majalah sebenarnya ini cukup lengkap. Ada delapan unit komputer, sebuah scanner dan laser printer. Kantornya luas yang disediakan Untaet di daerah elit Farol, di tengah kota Dili, dan ada sejumlah sepeda motor sumbangan USAID. Seperti juga Lian Maubere, Talitakum menerima sumbangan uang untuk gaji selama tiga bulan dari USAID.
Hampir semua pengelola Talitakum, seperti layaknya anak-anak muda di Indonesia, kebanyakan kekiri-kirian, kendati mereka berasal dari kalangan borjuasi Timor. Talitakum, memilih wilayah liputan di seputar penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan Untaet. Majalah ini cukup kritis terhadap Untaet, namun tidak kritis terhadap elit politik nasional Timor Timur dan sangat anti pada orang-orang yang dulu pro Indonesia.
SALVADOR Ximenes Soares memimpin harian Suara Timor Lorosa’e (STL), reinkarnasi harian Suara Timor Timr. STL menggunakan bahasa Indonesia, diselingi sedikit berita berbahasa Inggris, Portugis dan Tetum. Saya mengunjungi kantor itu tengah malam, berbincang-bincang dengan Salvador Soares dan beberapa redaktur hingga pagi hari. Kantor STL merupakan bangunan baru di belakang bangunan kantor STT yang hancur. Nama jalan di depan kantor STT sudah diganti jadi Avenida Martires da Patria, atau Jalan Pahlawan Negara. “Gedung baru ini bantuan pemerintah Kanada dan Australia,” kata Salvador.
Salvador merupakan tokoh kontroversial dalam sejarah politik dan pers Timor Timur. Sikap politiknya pro Indonesia, lalu direkrut Golongan Karya jadi anggota parlemen, namun di-recall karena dianggap tidak sungguh-sungguh membela integrasi. Dia memulai karir sebagai penyiar Radio Republik Indonesia Dili.
Abilio Soares, gubernur Timor Timur paling bontot sebelum daerah ini lepas dari Indonesia pada September 1999, mengajaknya menerbitkan harian STT. Maksud penerbitan itu jelas: sebagai suara integrasi. Namun, di tangan para wartawan muda, STT jadi harian yang galak, Abilio Soares diserang dan tentara dikritik. Ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi pada setiap suratkabar. Abilio berang dan memutuskan hubungan, termasuk melakukan boikot. Harian itu kehilangan ratusan pelanggan dari para pegawai pemerintah daerah.
Sebagai pendukung integrasi, Salvador Soares memang tak semilitan Francisco Xavier da Cruz, yang kini jadi diplomat, atau Eurico Gutteres, pemimpin milisi Timor Timur yang selalu mengatakan “rela mati untuk Merah-Putih.” Di media massa, atau di seminar-seminar, dia biasanya bicara cukup kritis tentang integrasi, kendati tidak secara terbuka. Tapi para aktifis dari Aliansi Jurnalis Independen, Salvador Soares dikecam sebagai tokoh yang menggunakan media untuk kepentingan politiknya, terutama di seputar jajak pendapat. Salvador Soares dituduh mengubah STT menjadi media untuk memenangkan referendum. “Situasi ketika itu memaksa saya,” ujarnya.
Sebelumnya, berita-berita STT memang condong ke prokemerdekaan, maklum, sebagian besar jurnalisnya pendukung kemerdekaan. Salvador Soares sama sekali tidak mencampuri urusan redaksi, sampai kantor koran itu dirusak sekelompok milisi prokemerdekaan. Para jurnalisnya kocar-kacir. Sembilan hari kemudian, koran itu terbit dengan dukungan penuh pada prointegrasi. Jajak pendapat diumumkan, Indonesia kalah, bumi hangus dijalankan. Kantor STT dibakar. Salvador mengungsi ke Jakarta.
Pasukan Interfet, pasukan multinasional, segera menguasai wilayah itu, dan pemerintahan transisi PBB disiapkan. Tak ada koran yang terbit, sampai sejumlah jurnalis STT yang pulang dari pengungsian, menerbitkan Timor Post. Koran ini mula-mula terbit mingguan, seukuran kuarto, dan difotocopi. Pertama kali terbit dan dibagi gratis ketika Presiden Indonesia Abdurahman Wahid mengunjungi Dili. “Kami patungan untuk memperbanyak koran ini,” ujar Laurenco Martins, redaktur harian itu.
Laurenco dulu wartawan STT, ditugaskan di lingkungan militer. Dia kenal banyak perwira tentara, mengikuti kunjungan para komandan ke berbagai pelosok Timor Timur, dan naik-turun helikopter tentara. Tapi, di seputar jajak pendapat, dia menjadi salah satu musuh yang harus dibunuh. Di Bobonaro, rumah keluarga Martins dirusak massa prointegrasi yang dipimpin komandan militer setempat. Di Dili, dia bersembunyi karena dikejar milisi. “Sejumlah polisi Indonesia mengawal saya dan wartawan lain ke airport. Saya lega ketika turun di Surabaya lalu melanjutkan perjalanan ke Jakarta,” kenangnya.
Laurenco bersama hampir semua jurnalis STT bergabung di Timor Post. Pemimpin harian ini, Hugo da Costa, wartawan senior yang dipilih teman-temannya menjadi pemimpin redaksi. Anak muda prokemerdekaan ini memang paling menonjol. Dulu, dia satu kamar dengan saya. Tiap pagi, dia selalu memutar lagu-lagu perjuangan kemerdekaan Timor berbahasa Tetum.
Timor Post berkantor di bekas gedung balai prajurit Tentara Nasional Indonesia pemberian Untaet. Modalnya dari USAID. Untaet mendukung koran ini dengan memasang semua iklan di harian ini. Oplah harian ini hanya 800 eskemplar tiap hari. STL lebih besar, sekitar 1.700 eksemplar tiap hari. “Susah menembus 2.000 eksemplar,” kata Salvador.
Salvador kembali ke Dili atas ajakan Xanana Gusmão dan Ramos-Horta. Dalam dua pertemuan di Singapura, dua tokoh prokemerdekaan ini meminta Salvador untuk menerbitkan harian. Salvador semula ragu-ragu. Dalam pertemuan berikutnya di Australia, Gusmao dan Ramos-Horta mengulangi permintaan itu. “Apakah orang Timor masih menerima saya?” Salvador bertanya kepada Xanana dan Ramos-Horta. Dua orang ini memberikan jaminan. “Kalau perlu saya akan jadi pelindung yayasan penerbit koran itu nanti,” jawab Xanana.
Salvador masih ragu. Kebencian orang-orang prokemerdekaan pada para tokoh prointegrasi belum hilang. Namun jaminan Xanana dan Ramos-Horta mendorongnya pulang, menjajaki penerbitan koran baru itu. Apalagi Timor Post sudah terbit dan diterima masyarakat. Timor Post akan menjadi pesaing yang berat, apalagi koran itu tak berbau integrasi.
STL terbit 25 Mei 2000, Senin hingga Sabtu. Selama dua bulan, Valens Doy, lagi-lagi turun tangan, mempersiapkan penerbitan itu. Mula-mula orang Timor menaruh curiga dengan terbitnya STL. “Salvador bikin apa itu?” selidik Uskup Belo. Namun, akhirnya, STL bisa diterima. Orang Timor itu pemaaf. Salvador bahkan ditunjuk jadi anggota Dewan Nasional Timor Lorosa’e. “Rekonsiliasi bisa dimulai dari kalangan media,” ujar Metta Gutteres, wartawan STL.
Tidak mudah menerbitkan media cetak di wilayah ini, selain sumber daya manusia yang jauh dari kurang, media massa cetak menghadapi masalah tiadanya prospek bisnis. Penduduk hanya 500 ribu, sebagian besar penganggur dan petani miskin. Lalu, kemampuan membaca kurang.
Kehadiran orang-orang asing yang bekerja untuk Untaet dan lembaga-lembaga nonpemerintah internasional, yang jumlahnya mencapai 10 ribu orang dengan penghasilan yang cukup tinggi, sekitar US$5.000 hingga US$10 ribu sebulan, tidak secara otomatis mengisi pasar.
Belanja iklan didominasi iklan-iklan Untaet dan perusahaan-perusahaan asing yang melayani orang-orang asing. Dibanding di zaman Indonesia, belanja iklan di zaman Untaet lebih banyak dan dibayar dengan dolar Amerika Serikat dan Australia. Untuk sementara, iklan-iklan ini sangat membantu. Namun, jika tugas-tugas Untaet selesai dan perusahaan-perusahaan asing menutup usahanya, apa yang akan terjadi? Belanja iklan akan menurun drastis, dan daya serap pasar pembaca akan mengecil. Sekarang saja, STL sebuah harian nasional yang terbit di ibukota, menurut Salvador Soares, hanya mampu menjual korannya sebanyak 1.700 eksemplar sehari. Mungkin STL, demikian juga Timor Post yang hanya mencetak 1.000 eksemplar sehari, merupakan surat kabar nasional terkecil oplahnya di dunia.
VIRGILIO da Silva adalah sosok lain. Dia salah seorang pendiri majalah Talitakum, lalu mengundurkan diri dan menerbitkan tabloid Lalenok, surat kabar berbahasa Tetum. Gil, demikian dia biasa disapa, lulusan sebuah universitas di Yogyakarta. “Menerbitkan suratkabar berbahasa Tetum mula-mula ditertawakan banyak orang,” ujar Gil.
Bahasa Tetum memang agak rumit, strukturnya mirip bahasa Jawa atau Sunda. Banyak ragamnya, ada Tetum Terik yang sangat halus ada pula Tetum Dili yang sudah mengalami percampuran. Selain Tetum, Timor memiliki sekitar 30 bahasa daerah. Orang-orang Lospalos tidak menggunakan Tetum. Anak-anak di Maubessi malah tidak mengenalnya. Lalenok menggunakan Tetum Terik. “Tetum Dili tidak bisa dipakai untuk suratkabar berita. Tetum Dili itu seperti Bahasa Indonesia gaya Jakarta,” tambah Gil.
Tetum Terik tak gampang dimengerti. Seorang pembaca menelepon, dia membutuhkan waktu seminggu untuk membaca Lalenok, padahal tabloid itu tak tebal, hanya 20 halaman. Saya bertemu dengan tujuh staf redaksi Lalenok di kantor mereka yang berhalaman luas bekas wisma Angkatan Laut Indonesia. Mereka bilang, media berbahasa Tetum sangat penting untuk mendorong pemakaian bahasa itu agar dipakai sebagai bahasa nasional.
Di Timor Timur kini tengah terjadi silang pendapat tentang bahasa nasional yang digunakan. Tokoh-tokoh politik seperti Ramos-Horta, Xanana, Mar’ie Alkatiri, dan orang-orang yang datang dari luar negeri mendesakkan kemauannya agar bahasa Portugis dipakai sebagai bahasa resmi negara dan bahasa Tetum menjadi bahasa kedua. “Anak-anak muda terpelajar menolaknya, mereka memilih bahasa Tetum sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua,” kara Gil.
Alasan mereka, hanya sedikit orang Timor yang bisa berbahasa Portugis. Mereka biasanya pernah mengenyam pendidikan seminari, yakni pendidikan calon pastor yang mewajibkan siswanya berbahasa Portugis. Lalenok kemudian jadi semacam media yang ingin mendesakkan kebutuhan akan pentingnya bahasa Tetum sebagai bahasa nasional.
Namun musuh Lalenok cukup banyak. Salah satunya pemerintah Portugal. Negeri itu ingin berpengaruh lagi dengan mengirim guru-guru bahasa Portugis, memberi kursus gratis di mana-mana. Timor Lorosa’e bukan Portugis. Orang-orang Untaet tampaknya mencium gelagat tak enak. Mereka memutuskan, pengajaran di sekolah dasar menggunakan bahasa Tetum. Namun, radio Untaet masih memberi ruang untuk siaran seksi Bahasa Portugis, kendati bahasa Indonesia juga memperoleh porsi yang banyak.. Televisi Untaet malah menjalin kerjasama dengan Metro TV, menyiarkan kembali berita-berita dari stasiun televisi Jakarta itu.
Ketika kembali lagi ke Jakarta, kali ini saya tak merasa sedih, tapi sadar bahwa orang-orang seperti Gil punya tugas yang maha berat. ***